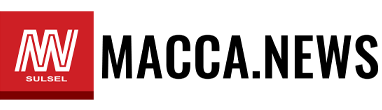Oleh: Musakkir
Demokrasi yang tak pernah selesai dibincangkan, dari Socrates (335 SM), hingga era pertengahan bahkan memasuki era politik modern, persoalan demokrasi belum menemui kesimpulannya. Terus dibicarakan baik ditingkat grass root maupun ditingkat elit. Yah, benar ungkapan Francis Fukuyama, bahwa demokrasi menjadi perkara ummat sejagat.
Karenanya, demokrasi selalu bersesuaian dengan mandat rakyat sebagaimana makna demos-kratos. oleh sebab itu, demokrasi yang dipahami sebagai proses politik rakyat tentu sedapat mungkin dapat bersinggungan dengan berbagai kepentingan rakyat. Tetapi, soal demokrasi kerapkali bersinggungan dengan local community, seperti kemiskinan, kesehatan dan pendidikan.
Demokrasi yang dipahamkan sebagai tolok ukur proses berpolitik yang ideal, maka sejatinya demokrasi memberi : (1) ruang ekspresi bagi masyarakatnya terkait dengan mimbar kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. (2) ruang ekspektasi bagi setiap warga negaranya di dalam mewujudkan kapabilitasnya demi mewujudkan pemimpjn yang baik bagi masyarakatnya. (3) Paling tidak demokrasi tetaplah harus disimbolkan sebagai makna kebebasan. Dengan demikian maka masyarakat tak.lagi merasa terkurung (imanensi) dalam berbagai lingkungannya.
Dibanyak fenomena, politik yang selama kurang lebih 32 tahun lamanya terkurung (sentralistik), problem demokratik demikian besar tantangannya. Sebab masa itu, begitu terasa despotisme politik dan gaya kepemimpinan yang otoriterianisme, sangat menghambat demokrasi. Kebebasan terpasung.
Namun reformasi 98 telah menggulung otoriterianisme menjadi politik yang serba terbuka, transparansi dan accountabilitas digelorakan sebagai bagian dari agenda perubahan. Tetapi, fase berlanjut tanpa sadar, reformasi gagal, sebab prilaku korupsi terjadi dihampir elemen pemerintahan baik itu kepala daerah (eksekutif) maupun anggota DPR (legislatif), bahkan termasuk di jajaran penegak hukum. Inikah yang disebut paradoks ?
Dari sinilah kemudian demokrasi di bully, di sandera bahkan dikurung oleh kepentingan politik yang lebih besar. Realitas ini kemudian turun sampai ke level pilkada gubernur, walikota maupun kabupaten. Parpol pun mengalami “kecemasan” antara memilih kadernya atau terpaksa membeli “tokoh” dari luar partai. Terus, kalau demikian prakteknya, maka dimana sesungguhnya eksistensi dan proses kaderisasi didalam partai, ataukah parpol tidak percaya diri ? semua itu kembali menjadi tantangan bagi parpol untuk menjelaskan ke publik.
Dan sangat ironis, pada proses transaksional politik antar partai, maka berkecendrungan *mengurung demokrasi*. Ketokohan tersandera karena tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli kendaraan (parpol). Lalu, kemana demokrasi itu di kurung ? sangat mungkin demokrasi itu dikurung oleh para bandar, bandit, dan mafia politik, dan kalau ini ter(jadi), maka akan melahirkan pemimpin seperti badut, bahkan seperti wayang yang di kendalikan oleh dalangnya. **semoga tidak terjadi. (*)