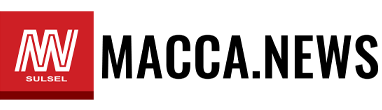Oleh : Saifuddin Al Mughniy
(Pendiri OGIEN Institute Research and Political Development)
Mungkin tulisan ini tidak terlalu menarik untuk dibaca, dan boleh jadi sebagian kita menyimak judulnya sedikit alay atau bahkan terlalu pesimis dan penuh kecurigaan.
Tapi semua itu sah-sah saja didalam memberikan hak kebebasan berpendapat, dan secara ekstrim kita bisa saja menuduh terhadap apa yang mungkin diungkapkan oleh penulisnya. Tetapi harus dibilang bahwa segala sesuatu yang terlihat (konkrit), bahkan yang abstrak, tersingkap atau yang tersembunyi pada prinsipnya “bisa menjadi obyek wacana” yang pada akhirnya akan menjadi narasi yang apik terhadap hal yang mungkin pantas untuk dibahasakan.
Tapi saya dan kita tak perlu jauh melompat pada satu “debat diskursus” pada hal-hal yang berbau filsafat yang kadang menyita waktu untuk memahaminya pada kedalaman yang bersifat “ontologicum”. Tetapi, makna “demokrasi dan ke(cemas)an adalah hal yang krusial yang tak pernah henti dibincangkan. Demokrasi yang tidak cukuo diartikulasikan sebagai demos dan kratos, namun dibalik kata demokrasi ada keluhuran, nilai, budaya, estetik, humanity, serta perilaku yang bertujuan menghadirkan kebaikan baik secara personal maupun secara kolektivitas.
Demokrasi yang seharusnya dipahami sebagai nilai dasar dalam membangun relasi dalam bernegara, berbangsa, bermasyarakat dan beragama, justru mendapat “kecurigaan dan tuduhan” yang beragam cara. Walau semua itu tidak seluruhnya benar. Maka benarlah pandangan Sigmund Freud dalam bukunya “Naluri Kekuasaan” yang ditulis oleh Calvin S. Hall. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa kecemasan dapat terjadi ketika suatu lingkungan tak lagi ditegakkan hukum dan nilai, serta prinsip kebudayaan yang ada. Maka bisa disebut bahwa saat ini kita sedang berada dalam suasana kecemasan.
Kecemasan begitu terasa dengan berbagai macam peristiwa dan pemberitaan. Di hampir semua sudut kota terpampang berbagai macam spanduk yang bertuliskan kami Indonesia, NKRI harga mati, Jempol untuk NKRI dan beberapa kalimat termasuk isu terorisme. Hal ini kalau diperhatikan tersimpang makna bahwa apakah bangsa ini memang berada dalam kecemasan ? ataukah hanya kecemasan secara politik sehingga “realitas” cendrung dikonstruksi menjadi majas yang mencemaskan. Negara setidaknya memberi rasa aman bagi warga negaranya, tidak harus membawa publik ke ruang diskursus yang mencekam.
Dalam perspektif sosial, demokrasi sebagai sistem ketatanegaraan, sehingga paling tidak kultur demokrasi tetap harus terpelihara sebagai bagian dari sistem politik yang demokratis. Proses berdemokrasi sebagaimana perhelatan politik seperti Pilkada serentak sejak tahun 2015, 2017 hingga 2018 menjadi fenomena menarik sebab wajah demokrasi semakin beragam. Belum lagi fenomena kolom kosong yang menang di kota Makassar. Kalau bisa di ibaratkan bahwa wajah demokrasi di Makassar seperti penuh “bintik dan noda”, walau harus dipahami bahwa demokrasi adalah tatanan atas nilai-nilai yang universal.
Oleh sebab itu, kecemasan atas nama demokrasi dapat disebabkan oleh beberapa hal, pertama, karena hasrat ambigu kekuasaan menyebabkan ada perasaan takut akan kekalahan sebelum kompetisi dilaksanakan. Sehingga memunculkan ke khawatiran kelompok atas kontekstasi politik. Kedua, bisa sangat diakibatkan oleh karena terseretnya varian ideologi dan agama pada kepentingan politik tertentu. Ketiga, karena tingkat kepercayaan publik yang semakin rendah terhadap partai politik, pemerintah dan negara. Keempat, trauma kekalahan secara politis, sehingga terjadi pengguringan opini yang menyesatkan. Kelima, fakta politik terjadi diluar dugaan, logika politik melampaui akal sehat kita.
Dengan demikian, maka untuk mengurai kecemasan tentu dengan upaya meminimalisasi berita Hoax (berita bohong), dan sedapat mungkin dapat membangun kesadaran dan kedewasaan ber-politik dengan transformasi pengetahuan yang lebih kontinew (berkelanjutan).